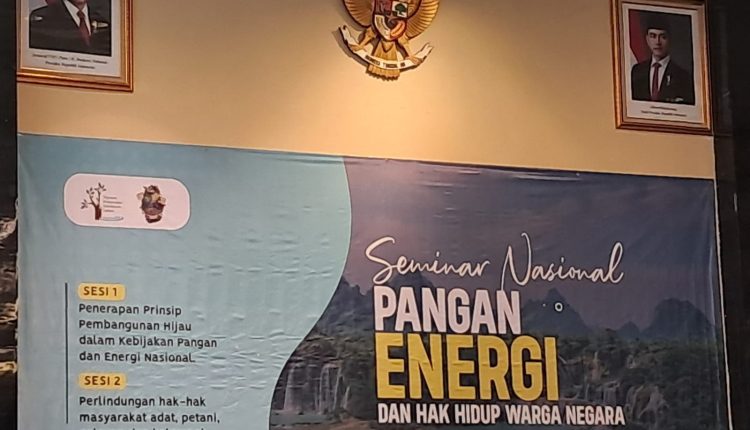Oleh: Sani Lake
Saya tiba di Hotel A-One Jakarta Pusat pagi itu, 11 November 2025, dengan perasaan yang sulit saya jelaskan. Di luar gedung, hiruk pikuk lalu lintas ibu kota seperti biasa bergerak tergesa-gesa, seolah tak pernah sempat menoleh pada nasib kampung-kampung yang jauh di tepian negeri. Tetapi di dalam ruangan itu, yang dinginnya AC mengalahkan angin pegunungan Kalimantan, suara-suara yang selama ini tersisih justru menemukan ruang untuk pulang.
YMKL menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Pangan, Energi dan Hak Hidup Warga Negara, Penerapan Prinsip Pembangunan Hijau dalam Kebijakan Nasional”. Konon, pemerintah ingin mempercepat pembangunan hijau dalam kerangka Asta Cita, khususnya swasembada pangan dan energi. Namun, di balik jargon hijau itu, para pembicara, peneliti, pembela lingkungan, komunitas pers dan utusan masyarakat dari berbagai pulau membawa cerita yang menantang apa yang disebut “Hijau”.
Saya duduk, membuka buku catatan dan mulai menuliskan setiap percikan suara yang muncul. Selebihnya, saya menyerap apa yang tidak tertulis, tatapan mereka, frasa-frasa yang tercekat di tenggorokan dan raut wajah mereka yang membawa pengalaman panjang dari kampung masing-masing.
Tembok Hijau yang Retak, Ketika Pembangunan Tak Lagi Manusiawi
Paparan pertama mengingatkan bahwa Asta Cita pemerintah, yang semestinya menempatkan HAM dan demokrasi sebagai fondasi Pembangunan, ternyata bergeser menjadi agenda besar swasembada pangan dan energi, yang dikerjakan lewat proyek-proyek raksasa. Di layar, saya melihat data yang tak mudah ditelan. Ada jutaan hektare lahan berubah menjadi konsesi industry. Ada pula jutaan warga kehilangan ruang hidup, selain ribuan petani terjerat konflik agraria.
Seorang narasumber mengutip laporan terbaru, dimana ada 61,3 persen petani kini berstatus gurem, mereka memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare. Sedangkan proyek energi berbasis nikel dan batu bara merayap masuk ke sawah-sawah subur.
Saya teringat Matarah, sebuah kampung kecil di Barito Timur, tempat para perempuan dan laki-laki pernah menanam padi merah di ladang-ladang yang kini dikepung izin tambang. Betapa ironi ketika negara berteriak soal “Kedaulatan Pangan”, sambil merampas tanah yang menyimpan sumber pangan itu sendiri.
Hak Asasi Manusia, Bukan Lampiran dari Pembangunan
Saurlin P Siagian dari Komnas HAM naik ke panggung dengan paparan yang tenang, tapi sangat tajam. Ia berbicara tentang SNP (Standar Norma Pengaturan) No. 15 Tahun 2024 yang menjadi dasar hukum baru untuk perlindungan masyarakat adat.
Menurutnya, pembangunan hijau hanya akan menjadi ilusi jika hak atas tanah, air, pangan, dan lingkungan hidup tidak dimasukkan ke jantung kebijakan. Negara tidak bisa memaknai lingkungan hanya sebagai sumber daya ekonomi. Ada manusia, ada sejarah, ada tubuh-tubuh yang bergantung pada tanah itu.
Kalimatnya yang paling saya ingat, “Keadilan ekologis tanpa keadilan manusia hanyalah slogan kosong”.
Di kursi belakang, saya melihat beberapa peserta mengangguk pelan. Barangkali karena kalimat itu serupa dengan pengalaman mereka.
Dari Batu Bara ke Nikel, Transisi atau Kolonialisme Baru?
Kemudian, giliran Muhammad Jamil dari JATAM berbicara. Ia tidak memulai dengan teori, tetapi dengan sebuah cerita dari Halmahera. Sungai Sagea, air yang bening dan menjadi kehidupan bagi kampung-kampung di sekitarnya, kini berubah. Limbah dari industri pengolahan nikel merayap ke dalam sungai. Masyarakat kehilangan sumber air dan anak-anak mandi di sungai yang berubah menjadi keruh.
Jamil menajamkan kritiknya dengan satu frasa, “Ini bukan transisi energi, ini transisi kolonialisme dari hitam ke hijau semu”.
Ia memaparkan data ke layer, ada 19 persen sawah nasional telah terdampak tambang, ada pula 1,7 juta ton beras hilang setiap tahun, sementara itu produksi pangan terancam runtuh ketika tambang dan smelter menyusup sampai ke wilayah pertanian. Di bagian lain Indonesia, orang kehabisan sawah, sedangkan di forum internasional, negara terus saja memamerkan ambisi menjadi “Pionir Transisi Energi”.
Saya mulai bertanya dalam hati, jika ini “pembangunan hijau”, lalu hijau itu untuk siapa?
WALHI, Melindungi Mereka yang Melindungi Bumi
Teo Reffelsen dari WALHI kemudian memperkuat benang merah diskusi: para pembela lingkungan hidup justru menjadi kelompok yang paling rentan. Ia menyebut SLAPP, intimidasi, kekerasan, hingga pembunuhan yang menimpa aktivis dan masyarakat.
Putusan MK terbaru memperluas perlindungan hukum, tetapi di lapangan aparat justru sering kali berdiri di pihak korporasi.
Dalam nada berat, Teo mengatakan: “Ketika pembela lingkungan diserang, itu berarti bumi sedang diserang”.
Bagi masyarakat kampung, perjuangan mempertahankan tanah bukan sekadar urusan hak, tapi urusan hidup dan mati. Inilah yang jarang disadari mereka yang membuat kebijakan dari gedung bertingkat.
Pengakuan yang Terbatas, Catatan dari KemenLHK dan AMAN
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memaparkan capaian pengakuan 164 masyarakat adat dengan luas wilayah ratusan ribu hektare. Tetapi prosesnya berbelit dan bergantung pada perda.
Seorang peserta dari kampung dengan pelan bicara, “Pengakuan itu baik, tapi kalau prosesnya lambat, hutan adat kami sudah habis duluan”.
AMAN kemudian mempertegas kritik itu, pengakuan di Indonesia bersifat deklaratif, bukan substansial. Negara sering merasa memberi “Karunia”, padahal masyarakat adat telah ada jauh sebelum negara berdiri. Hak atas tanah bukan hadiah, tetapi identitas dan kehidupan.
Reforma Agraria, Janji yang Terus Ditunda
Paparan dari ATR/BPN dan KPA menunjukkan bahwa redistribusi tanah memang berjalan, tetapi sangat jauh dari cita-cita reforma agraria sejati. Konflik agraria bertambah, bukan berkurang. Data tumpang tindih masih menjadi mimpi buruk. Sedangkan banyak petani menjadi buruh di tanah yang dahulu milik mereka sendiri.
Saya merasa seminar itu seperti menonton film panjang tentang negeri yang lupa rumahnya sendiri.
Suara Kampung Menjadi Kompas bagi Pembangunan
Namun yang paling menyentuh bagi saya, dan mungkin juga bagi banyak peserta, adalah ketika utusan komunitas dari berbagai daerah berbicara. Suara mereka pelan tetapi penuh tenaga moral, Seorang pesert dari Kalimantan menceritakan sumur kampung yang mengering sejak bulldozer masuk. Seorang pemuda Papua menceritakan hutan sagu yang ditebang atas nama investasi energi. Warga Halmahera bertanya apakah negara menganggap kampung sebagai collateral damage dari ambisi global.
Dalam setiap kesaksian itu, saya melihat ironi pahit, bahwa mereka yang menjaga tanah dianggap sebagai penghalang Pembangunan, mereka yang paling tahu tentang keberlanjutan justru tidak pernah diminta bicara.
Apa yang Hijau dari Pembangunan yang Menghapus Kampung?
Di akhir seminar, saya merenung. Pembangunan hijau yang disampaikan pemerintah sering hanya hijau dalam presentasi PowerPoint. Karena pertanyaannya, Hijau mana yang dimaksud? Di atas tanah yang digunduli? Di atas ladang-ladang yang digusur? Atau hijau dalam laporan investor yang menunjuk grafik pertumbuhan?
Di forum itu, saya belajar bahwa pembangunan hijau sejati tidak bisa lahir dari kerangka teknokratis, tetapi dari pengalaman rakyat yang mempertahankan tanah, air, dan pangan.
Seorang peserta lain mengatakan, “Di kampung kami, hijau itu bukan skema pemerintah. Hijau itu adalah kehidupan sehari-hari”.
Kalimat itu sekejap membuat jadi tenang, tetapi bagi saya, kalimat itu seperti cahaya yang menembus retakan tembok-tembok raksasa pembangunan.
Dari Ruang Hotel Kembali ke Kampung
Ketika saya keluar dari ruang seminar, Jakarta kembali dengan riuhnya. Tapi saya membawa pulang sesuatu yang lain, bahwa suara-suara dari kampung itulah yang semestinya menjadi kompas pembangunan negara. Bahwa transisi energi dan pangan bukan soal proyek raksasa, tapi tentang apakah rakyat masih bisa hidup di tanahnya sendiri.
Seminar itu bukan hanya forum intelektual, tetapi sebuah pengingat bahwa hak hidup warga negara bukan opsi, melainkan fondasi.
Dan mungkin, esai ini adalah cara saya menyimpan suara-suara itu, suara yang barangkali tidak pernah terdengar jelas di ruang-ruang kekuasaan, tetapi justru menjadi pijakan moral bagi masa depan negeri.
*Pegiat JPIC Kalimantan